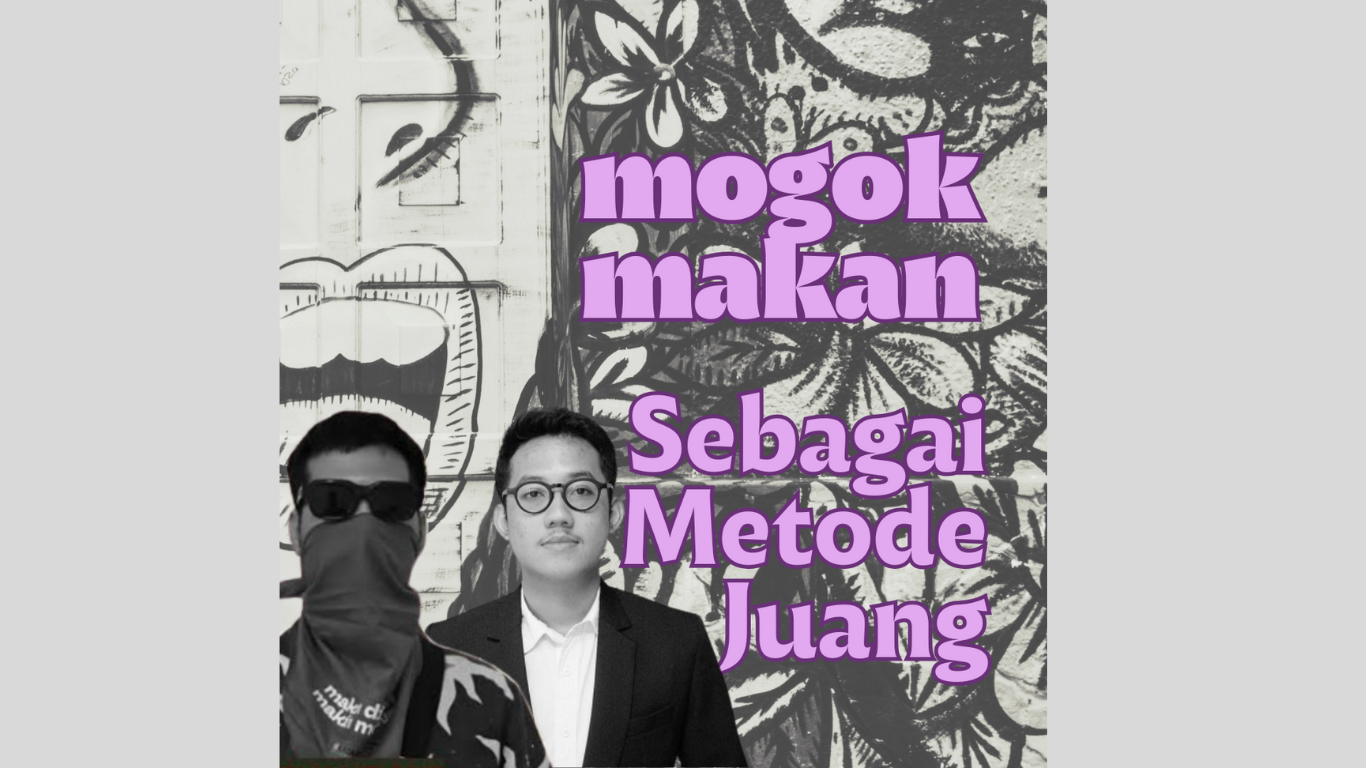Pangan, Bukan Cuma Soal Makan
Bertepatan dengan momen Hari Pangan Sedunia, yang jatuh setiap 16 Oktober, Solidaritas Perempuan dari berbagai wilayah menyatakan sikap melawan perampasan ruang hidup demi kedaulatan pangan kaum perempuan.
“Pangan itu bukan cuma soal makan,” ujar Linda Tagie, dari Serikat Perempuan (SP) Nusa Tenggara Timur. “Ia terhubung dengan sosial, politik, dan budaya. Karena itu negara wajib berpihak pada perempuan untuk mengelola ruang hidupnya secara berdaulat.”
Sayang, negara justru mengambil kebijakan politik yang berkontradiksi dengan hak perempuan atas ruang hidup dengan disahkannya UU Cipta Kerja yang melegalkan perampasan lahan untuk kepentingan kapital.
“UU Cipta Kerja menjadi payung hukum bagi perampasan ruang hidup. Undang-undang itu harus dicabut,” tegasnya.
Ia mengambil contoh, kebijakan geothermal di Poco Leok, Nusa Tenggara, yang merampas ruang hidup perempuan di sekitar. Tidak diam, kaum perempuan di Poco Leok menanam sayur, jagung, dan kacang-kacangan tanpa pestisida. Mereka menyebutnya kebun kolektif organik — bukan sekadar tempat bercocok tanam, tetapi ruang hidup yang mereka pertahankan dari perampasan.
Pengakuan.
Contoh lainnya adalah program Makan Bergizi Gratis yang sarat dengan kepentingan politik dan menihilkan peran perempuan. Pengetahuan perempuan dalam mengelola pangan, sama sekali diabaikan dan tidak berbasis komunitas.
Perempuan Sebagai Subyek Kedaulatan Pangan
Hal senada disampaikan Tami dari SP Lampung. Ia menuturkan bagaimana liberalisasi pangan dan kebijakan impor yang disahkan melalui UU Cipta Kerja telah meminggirkan pangan lokal yang selama ini dikelola kaum perempuan. Dengan demikian, peminggiran pangan lokal secara sekaligus menyingkirkan perempuan dari akses pengelolaan pangan. Akibat kebijakan impor, banyak pangan lokal tidak sanggup bersaing sehingga makin punah.
Hal ini juga menimpa keberadaan benih lokal yang kian langka akibat Peraturan daerah yang menyeragamkan benih. “Benih lokal tak lagi dilestarikan karena semua diatur dari atas,” kata Tami. “Padahal, hilangnya benih lokal berarti hilangnya pengetahuan perempuan tentang pangan.”
Sementara, peran perempuan sebagai petani tak kunjung memperoleh pengakuan. Alat pertanian modern tidak dirancang untuk nyaman dioperasikan oleh tubuh perempuan. Sehingga, kaum perempuan tersingkir dari proses bertani. Pun, kelompok tani yang kerap merumuskan kebijakan terkait pengelolaan pangan, distribusi, pengadaan benih lebih banyak didominasi laki – laki. Akibatnya, perempuan kehilangan akses terhadap benih, pupuk dan proses pengambilan keputusan.
“Ketika perempuan tak diakui sebagai petani, mereka tak punya suara dalam menentukan pangan,” kata Tami. “Padahal, mereka yang paling tahu cara bertahan.”
Di sisi lain, panjangnya rantai distribusi menambah beban perempuan tani. Untuk sampai ke konsumen, produk tani harus melalui para tengkulak. Tak heran, harga produk tani, singkong misalnya, jatuh akibat tengkulak menguasai pasar.
“Petani meminjam uang untuk menanam, tapi saat panen harga tak sepadan. Akhirnya rugi dan miskin lagi,” ujarnya.
Perubahan iklim membuat situasi makin tak menentu, dimana musim tanam sulit diprediksi, hasil panen makin sedikit.
Laut Kami Bukan Komoditas
Di pesisir Kendari, perempuan tak hanya menjaga dapur, tapi juga laut. “Perempuan pesisir adalah penjaga pangan laut. Kami mengelola, memimpin, dan berjuang mempertahankannya,” ujar Tinggo dari SP Kendari.
Ia menjelaskan, proyek reklamasi dan tambang yang difasilitasi oleh UU Cipta Kerja mengancam sumber penghidupan perempuan pesisir. “Laut kami bukan komoditas. Ia ruang hidup,” katanya.
Bagi perempuan Kendari, pangan lokal bukan hanya simbol budaya, tapi juga sumber ekonomi keluarga. Melalui praktik pangan lokal, mereka menunjukkan bahwa kedaulatan pangan berarti kemandirian dan pengakuan atas peran perempuan. Karena itu, mereka menuntut pencabutan UU Cipta Kerja yang membuka jalan bagi investasi yang merusak ekosistem pesisir.
Program Strategis Nasional (PSN): Politik Pangan Kapitalistik Anti Perempuan
Di Lombok Barat, pembangunan Bendungan Melinting, bagian dari Program Strategis Nasional (PSN), telah diklaim pemerintah sebagai proyek ketahanan air dan pangan. Namun bagi warga, terutama perempuan, proyek ini justru menciptakan krisis baru.
“Lahan produktif kami tergenang. Perempuan kehilangan pekerjaan dan sumber pangan,” ujar Yayuk dari SP Mataram.
Ia menyebut kebijakan reforma agraria yang dijalankan pemerintah hanya pro-rakyat di atas kertas. Faktanya, pembangunan dijalankan untuk investor. Pangan lokal hancur, perempuan kehilangan air dan gizi.
Bagi Yayuk, politik pangan pemerintah bersifat kapitalistik—mengutamakan produksi massal dan ekspor, bukan kedaulatan komunitas dan ekologi. “Perempuan miskin pedesaan paling terdampak karena bergantung pada air dan lahan lokal,” katanya.
Namun, di tengah keterbatasan, muncul perlawanan kecil tapi berarti. Perempuan di Dusun Bukit Tinggi membentuk kelompok perempuan bertani. Mereka menanam bibit lokal bukan untuk dijual, tetapi untuk bertahan hidup.
Pangan Adalah Politik
Suara dari berbagai wilayah itu berpadu dalam satu pesan bahwa pangan bukan sekadar urusan dapur, tapi juga politik ruang hidup. Kebijakan negara yang berpihak pada modal telah mencabut akar kehidupan perempuan dari tanah, laut, dan udara tempat mereka bergantung.
“Ketika politik pangan dijalankan dengan orientasi kapital, bukan komunitas, maka yang pertama tersingkir adalah perempuan,” ujar Linda Tagi menutup pembicaraan. “Karena itu, perjuangan kedaulatan pangan adalah perjuangan mempertahankan kehidupan itu sendiri.”
Demi kedaulatan pangan kaum perempuan, UU Cipta Kerja dan turunannya harus dicabut dan mengembalikan kedaulatan pangan kepada perempuan sebagai subjek pengelolaan pangan.