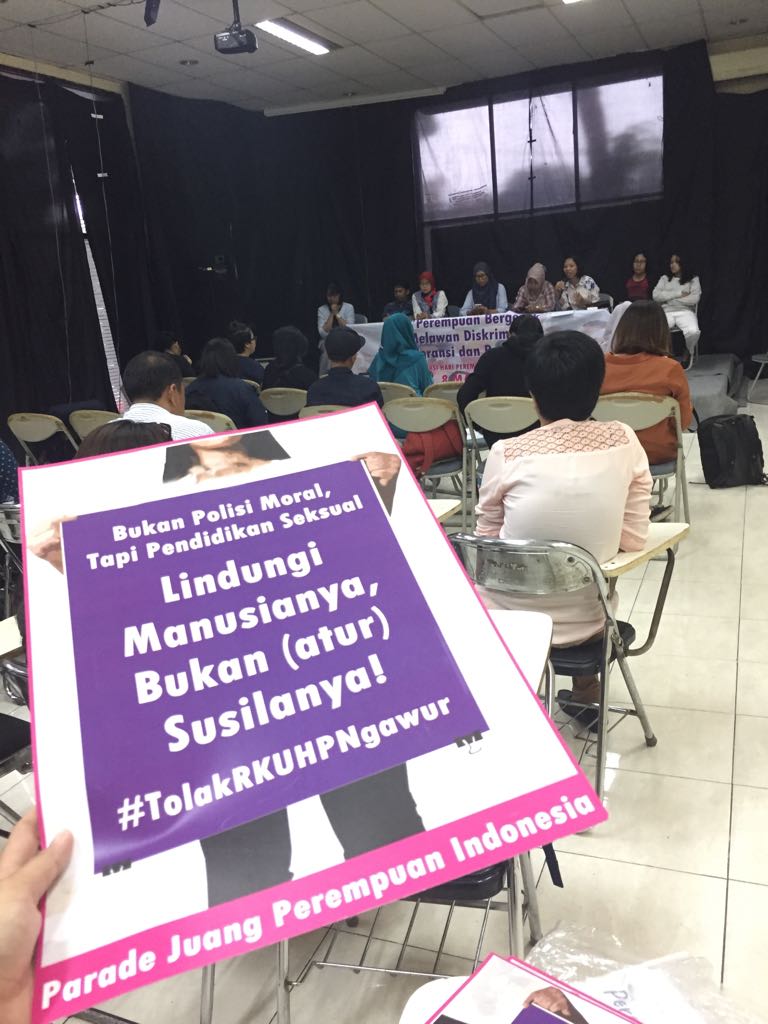Sore itu, di Plaza Promenade Taman Ismail Marzuki, udara Jakarta mengalun lembut di antara musik, tawa, dan obrolan santai. Di tengah lalu-lalang pengunjung, sekelompok orang duduk melingkar, berdiskusi tanpa jarak. Tidak ada panggung tinggi atau pembatas formal; suasananya cair, akrab, dan hangat—sebuah forum warga di mana siapa pun boleh bicara.
Acara bertajuk “Literasi Digital, Perempuan, dan Demokrasi” itu merupakan bagian dari program Klik Rakyat, gagasan Suara Ibu Indonesia dengan dukungan Dewan Kesenian Jakarta. Bukan sekadar diskusi, melainkan ruang temu yang dirancang sebagai mimbar rakyat: tempat masyarakat memikirkan ulang krisis demokrasi yang kini tidak hanya terjadi di jalanan, tapi juga di ruang digital.
“Aktivis, seniman, dan warga biasa—semua bisa bergerak. Demokrasi tidak akan bertahan kalau kita hanya jadi penonton,” ujar Mira Sahid dari Suara Ibu Indonesia, yang menjadi moderator sore itu.
Bagi Mira, perempuan bukan sekadar objek arus informasi digital, tetapi subjek penting dalam membangun budaya literasi yang beretika, berdaya, dan berpihak pada kemanusiaan.
Ketika Hoaks Menyamar Jadi Kebenaran
Sesi pertama dibuka oleh Puji F. Susanti dari Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO), yang menceritakan lahirnya gerakan mereka di tengah polarisasi politik dan ledakan hoaks di media sosial.
“Sejak awal, ruang digital sudah jadi arena konflik. Informasi salah menyebar begitu cepat, dan banyak orang kehilangan kemampuan memilah mana yang benar,” katanya.
Namun menurut Puji, tantangan literasi digital kini tidak berhenti pada kemampuan cek fakta. Ia menyangkut keselamatan, martabat, dan keadilan gender.
“Perempuan adalah kelompok paling rentan terhadap penyalahgunaan teknologi. Dari pelecehan verbal di kolom komentar sampai penyebaran foto tanpa izin, bahkan kini ada deepfake—manipulasi wajah dan suara dengan AI yang bisa menghancurkan reputasi seseorang,” tegasnya.
MAFINDO menaruh perhatian khusus pada keamanan digital bagi perempuan dengan konsep “CABE”: Cakep, Aman, Beretika. Artinya, perempuan harus cerdas menggunakan teknologi, paham risiko, dan mampu menjaga ruang digital tetap sehat.
Puji menambahkan, literasi digital dimulai dari rumah. “Kalau perempuan melek digital, satu keluarga ikut terlindungi. Karena ibu sering jadi sumber informasi pertama di rumah.”
Literasi Digital Sebagai Perjuangan Demokrasi
Dalam sesi berikutnya, Donny BU dari Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi mengajak peserta melihat literasi digital sebagai bagian dari perjuangan demokrasi.
“Sekarang demokrasi tidak hanya hidup di TPS, tapi juga di media sosial,”ujarnya. “Pertarungan opini, pembentukan persepsi publik, bahkan arah kebijakan negara—semuanya dimulai di dunia digital.”
Empat pilar literasi digital — cakep, aman, berbudaya, beretika — menurut Donny, bukan sekadar pedoman teknis, tapi strategi politik warga untuk mempertahankan kebebasan berpikir di tengah gempuran algoritma.
“Kalau kita tidak melek digital, kita bisa dimanipulasi. Demokrasi bisa dicuri diam-diam lewat layar ponsel.”
Donny juga menyoroti pentingnya kesetaraan dalam desain teknologi. “Kami di Siberkreasi punya prinsip gender balance by design. Kesetaraan tidak boleh ditambahkan di akhir, tapi harus dirancang sejak awal.”
Ia mengingatkan, algoritma media sosial cenderung memperkuat polarisasi. “Platform digital bekerja berdasarkan perhatian. Semakin marah orang, semakin lama mereka bertahan. Tapi kemarahan yang dipelihara terus justru mematikan dialog.”
Bagi Donny, literasi digital adalah kemampuan empatik dan etis untuk tetap manusiawi di tengah dunia yang serba otomatis.
Teknologi Tak Pernah Netral
Nada diskusi bergeser lebih dalam saat Blandina Lintang dari PurpleCode Collective berbicara. Suaranya lembut, tapi kata-katanya menohok. “Sering kita dengar kalimat: teknologi itu netral, tergantung siapa yang menggunakannya. Tapi kalau kita pakai kacamata feminis, kita tahu teknologi tidak pernah benar-benar netral.”
PurpleCode Collective, kelompok feminis yang berdiri sejak 2015, fokus pada relasi antara teknologi, gender, dan kekuasaan.Lintang memberi contoh sederhana namun tajam: “Kalau kita tulis di Google Translate ‘dia seorang dokter’, hasilnya sering ‘he is a doctor’. Tapi kalau ‘dia seorang perawat’, muncul ‘she is a nurse’. Itu contoh kecil bagaimana algoritma menyerap bias gender dari dunia nyata.”
AI, katanya, belajar dari data buatan manusia. Maka, jika dunia yang menciptakan data itu patriarkal, algoritma pun mewarisi bias yang sama. Masalahnya, kini AI digunakan untuk menentukan hal-hal penting: siapa yang berhak mendapat bantuan sosial, siapa yang dianggap berpotensi kriminal, bahkan siapa yang ‘layak’ diterima kerja. “Kalau datanya tidak inklusif, sistemnya akan menyingkirkan yang paling lemah.”
Bagi PurpleCode, literasi digital berarti membongkar relasi kuasa di balik layar. “Kalau kita tidak paham, kita akan jadi objek, bukan subjek dari teknologi. Dan itu berbahaya—karena algoritma bisa menjajah lebih halus daripada kekuasaan apa pun.”
Belajar dari Ibu Hesti dan Generasi WhatsApp
Suasana forum menjadi lebih hidup saat mikrofon berpindah ke tangan Ibu Hesti, ibu rumah tangga berusia 65 tahun. Dengan gaya lugas dan jujur, ia bercerita tentang pengalamannya menjaga “akal sehat” di grup WhatsApp keluarga.“
Saya sering banget dapat pesan yang kelihatannya hoaks. Saya bilang ke teman-teman: jangan asal sebar. Tapi malah saya yang dimarahi, dibilang sok tahu,” ujarnya, disambut tawa hangat peserta.
Tawa itu bukan sekadar hiburan; ia menjadi cermin bahwa literasi digital bukan hanya kemampuan teknis, tapi juga keterampilan sosial dan emosional. Menegur hoaks di grup keluarga berarti berhadapan dengan hierarki, sopan santun, bahkan risiko konflik. Di tangan perempuan seperti Ibu Hesti, literasi digital menjadi praktik keseharian—kerja sunyi yang menjaga demokrasi dari dalam rumah.
Dari Ruang Publik ke Ruang Digital
Bagi Suara Ibu Indonesia, forum Klik Rakyat bukan sekadar acara, tapi praktik demokrasi kecil: ruang percakapan setara di tengah dunia digital yang kian gaduh dan terfragmentasi.
“Kalau dulu kita bicara tentang suara rakyat di jalan, sekarang kita bicara tentang suara rakyat di layar,” kata Mira Sahid menutup diskusi.
Ruang digital hari ini adalah medan baru perjuangan politik, kultural, dan eksistensial. Siapa yang menguasai narasi di sana, dialah yang menentukan arah bangsa. Karena itu, literasi digital bukan lagi pilihan, melainkan syarat untuk bertahan sebagai warga yang merdeka.
Malam turun perlahan di Taman Ismail Marzuki. Lampu-lampu plaza menyala, memantulkan wajah-wajah peserta yang masih berbincang dalam kelompok kecil. Di antara mereka ada aktivis, jurnalis, mahasiswa, ibu rumah tangga, dan pegiat teknologi—berbeda latar, tapi satu keresahan: bagaimana menjaga agar ruang digital tidak menjadi tempat yang menindas, melainkan taman yang menumbuhkan.
Di penghujung acara, kalimat Lintang dari PurpleCode seolah menjadi penutup yang melekat di benak semua orang: “Teknologi bisa meniru, tapi tidak bisa mencipta empati. Itulah tugas kita — manusia — untuk menjaga agar demokrasi tetap punya hati.”