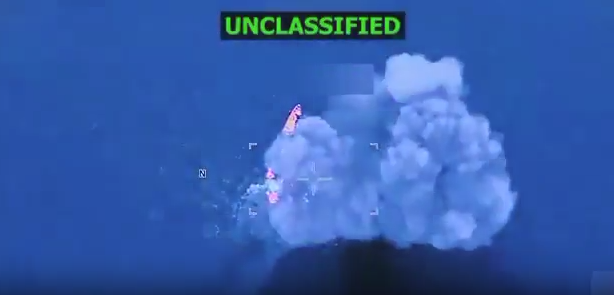Oleh Yuli Riswati
Suara yang Dipertentangkan
Di sebuah diskusi publik tentang gerakan anak muda, seorang aktivis senior dari era reformasi pernah mengeluh: “Gerakan sekarang ini tercerai-berai. Tidak ada pemimpin. Tidak ada organisasi. Hanya ikut tren media sosial.” Pernyataan seperti ini sering muncul dari generasi aktivis lama yang terbiasa dengan organisasi massa formal, struktur kepemimpinan yang jelas, dan garis ideologi yang tegas.
Namun, jika kita menengok realitas hari ini, mudah terlihat bahwa kepemimpinan tidak hilang, ia hanya berubah bentuk. Dari podium rapat akbar ke layar ponsel, dari pamflet ke TikTok, dari tokoh tunggal ke jaringan yang cair. Influencer, konten kreator, hingga admin akun kolektif kini memegang peran penting dalam membentuk opini, memobilisasi massa, bahkan menentukan arah politik.
Apakah ini berarti aktivisme mati? Justru sebaliknya: aktivisme sedang berevolusi.
Akar Ketegangan: Aktivis Jalanan vs Influencer Politik
Perbedaan paling menonjol antara aktivis “klasik” dan influencer terletak pada cara mereka membangun basis dan kepemimpinan.
- Aktivis jalanan tumbuh dengan disiplin organisasi, rapat panjang, ideologi yang dirumuskan lewat buku tebal dan dokumen politik. Kredibilitas mereka lahir dari konsistensi turun ke lapangan, menghadapi represi, dan membangun kaderisasi.
- Influencer politik mengandalkan jaringan digital. Basis mereka bukan anggota organisasi, melainkan follower. Kepemimpinan mereka lahir dari kemampuan menciptakan konten yang relevan, mudah dicerna, dan sesuai logika algoritma.
Kedua model ini sering dipertentangkan. Bagi sebagian aktivis, influencer dianggap dangkal: bicara tanpa risiko, hanya mengejar viralitas. Sebaliknya, bagi anak muda di era digital, organisasi klasik terasa lambat, kaku, bahkan eksklusif.
Padahal, kalau kita lihat lebih dalam, kedua model ini tidak bertentangan secara mutlak, mereka bisa saling melengkapi.
Reformasi Dikorupsi: Contoh Pertemuan Dua Dunia
Aksi #ReformasiDikorupsi pada September 2019 adalah salah satu bukti nyata. Ribuan mahasiswa turun ke jalan menolak revisi UU KPK dan RKUHP. Tapi daya ledaknya bukan hanya karena aksi fisik.
Di media sosial, khususnya Twitter dan Instagram, tagar #ReformasiDikorupsi meledak. Infografis buatan akun @penerbitbukabuku, @indonesiatanpafeminis.id (parodi), hingga konten singkat mahasiswa di TikTok memperluas jangkauan isu. Banyak orang yang tidak ikut turun aksi tetap tergerak menyuarakan penolakan dari rumah, berbagi konten, bahkan menggalang donasi logistik.
Di sini terlihat: aksi massa tetap penting, tetapi viralitas digital yang digerakkan influencer dan akun kolektif menjadi amplifier yang tak bisa diabaikan.
Gerakan 17+8: Warna, Musik, dan Imajinasi Baru
Gerakan 17+8 yang muncul tahun 2025 juga memperlihatkan logika baru kepemimpinan. Tanpa organisasi tunggal, tanpa ketua, gerakan ini menyebar melalui simbol warna pink-hijau, musik indie yang jadi anthem, dan konten kreatif di media sosial.
Alih-alih manifesto panjang, mereka menyampaikan sikap politik lewat poster digital, reels, dan video pendek. Alih-alih rapat resmi, mereka membangun konsensus lewat Discord, Telegram, atau obrolan santai di kafe.
Bagi aktivis lama, ini bisa tampak “main-main” atau “tidak serius”. Tapi faktanya, pola semacam ini membuat gerakan lebih cair, adaptif, dan sulit direpresi. Polisi bisa membubarkan aksi jalanan, tapi tidak bisa menghentikan banjir konten TikTok. Negara bisa menangkapi aktivis, tapi sulit menargetkan kepemimpinan yang tersebar di banyak akun anonim.
Rachel Vennya dan Politik Kepedulian
Contoh lain adalah kasus Rachel Vennya pada masa pandemi. Ia bukan aktivis, bahkan banyak yang menilai ia sekadar selebgram. Tapi ketika ia menggunakan platformnya untuk menggalang donasi bagi tenaga medis, respon publik luar biasa besar, jauh melampaui yang bisa dilakukan LSM atau serikat.
Memang, Rachel kemudian juga terjerat kontroversi (kabur dari karantina), tapi momen ini menunjukkan: influencer punya daya mobilisasi masif. Pertanyaannya: mengapa energi sebesar ini sering diremehkan oleh aktivis klasik?
Tsamara Amany dan Ruang Politik Formal
Kita juga bisa menengok Tsamara Amany, yang sempat menjadi ikon politik muda lewat PSI. Banyak yang mengenalnya bukan karena aksi lapangan, melainkan karena keberaniannya berbicara di televisi, YouTube, dan media sosial. Tsamara mewakili model kepemimpinan baru: politisi yang lahir dari panggung digital, bukan dari organisasi akar rumput tradisional.
Meski kemudian ia mundur dari politik formal, fenomena Tsamara menandai pergeseran: anak muda bisa membangun pengaruh politik lewat layar, bukan hanya lewat struktur partai atau organisasi massa.
Aktivisme Lingkungan dan HAM: Dari Jalan ke Timeline
Gerakan lingkungan juga sangat dipengaruhi model influencer. Pegiat muda seperti @FarwizaFarhan (Lingkungan Aceh), atau gerakan Save KPK, #PapuanLivesMatter, hingga isu gender yang sering diangkat akun kolektif feminis di Instagram, menunjukkan bahwa edukasi publik kini bergantung pada konten yang mudah dibagikan.
Aksi jalanan penting, tetapi narasi digital justru memberi daya tahan isu. Misalnya, kekerasan di Papua sering luput dari media arus utama, tapi kampanye digital membuatnya tetap hidup di kesadaran publik.
Kepemimpinan yang Berubah: Dari Struktur ke Jaringan
Jika dulu kepemimpinan berarti satu tokoh karismatik atau komite formal, kini kepemimpinan berarti:
- Distributed leadership: kepemimpinan tersebar di banyak akun, banyak figur, banyak ruang.
- Algorithmic leadership: yang menentukan visibilitas bukan rapat organisasi, tapi algoritma media sosial.
- Narrative leadership: kekuatan terletak pada siapa yang bisa menguasai narasi publik dengan cepat dan kreatif.
Inilah yang sering tidak dipahami oleh aktivis lama. Mereka melihat “tidak ada organisasi”, padahal organisasi kini hadir dalam bentuk lain: jaringan, komunitas online, dan ruang diskusi cair.
Tantangan dan Risiko
Tentu saja, model kepemimpinan digital tidak tanpa masalah. Ada risiko:
- Gerakan jadi dangkal, cepat viral tapi cepat hilang.
- Influencer bisa lebih peduli pada personal branding ketimbang agenda kolektif.
- Tanpa ideologi yang jelas, gerakan bisa mudah dibajak oleh kepentingan kapital atau politik elektoral.
Di sinilah aktivis klasik tetap punya peran: memberi kedalaman analisis, arah jangka panjang, dan konsistensi. Tapi mereka harus siap beradaptasi dengan metode baru.
Gerakan yang Menyebar Lintas Batas
Satu hal yang sering terlupakan adalah bagaimana gerakan di Indonesia kini tak hanya berdampak ke dalam negeri, tetapi juga menginspirasi di luar negeri. Dari Nepal, Filipina, hingga Prancis, anak muda Gen Z mengaku terinspirasi dari cara gerakan di Indonesia menyebar melalui media sosial. Imajinasi politik yang lahir di sini meresonansi ke gerakan lain, membuktikan bahwa energi anak muda bisa lintas batas negara.
Kesempurnaan Proses, Bukan Gerakan
Tak ada gerakan yang sempurna. Justru, kesempurnaan itu ada pada proses belajar satu sama lain, bagaimana generasi saling mendukung, bukan saling meremehkan. Aktivis senior atau orang-orang yang mengaku kiri tidak lagi relevan jika hanya sibuk nyinyir dan mengkritik anak muda dari kejauhan. Yang dibutuhkan adalah kehadiran mereka untuk memberi warna, ilmu, dan pengalaman, agar energi baru ini tidak hilang sia-sia.
Saatnya Meng-Upgrade Imajinasi Politik
Alih-alih mempertentangkan aktivis dan influencer, lebih produktif membayangkan bagaimana keduanya bisa bersinergi. Influencer adalah amplifier yang membuat isu didengar luas. Aktivis adalah arsitek yang memberi struktur dan strategi.
Gerakan anak muda hari ini tidak tercerai-berai; mereka hanya beroperasi dengan logika zaman mereka sendiri: cair, cepat, berbasis jaringan. Kepemimpinan tidak hilang, hanya berpindah dari podium ke layar, dari organisasi formal ke ruang digital.
Maka, tantangannya bukan lagi membuktikan siapa yang lebih “asli” atau “serius”, tapi bagaimana membangun jembatan antara dua dunia ini. Karena pada akhirnya, perubahan sosial tidak hanya lahir dari jalanan atau timeline, tapi dari keduanya yang saling menguatkan.